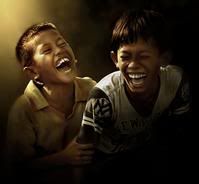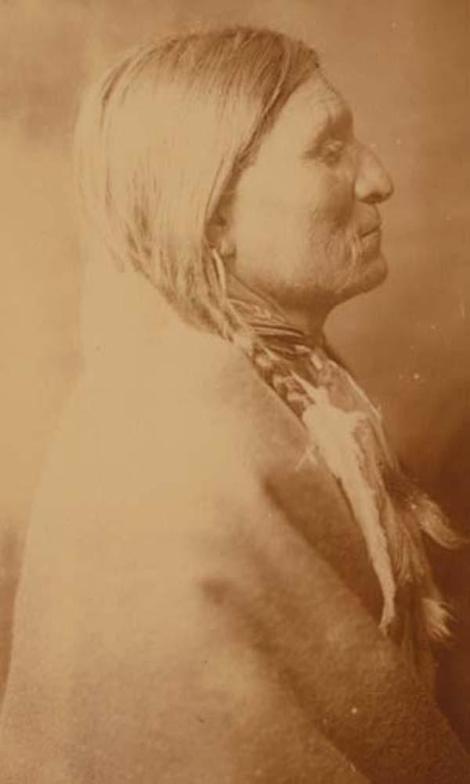Galuh Berarti Putri Bangsawan Atau Sejenis Batu Permata
Pengantar
Tanggal 16-19 Mei, di Tasikmalaya diadakan Seminar Sejarah dan Budaya II tentang Galuh. Seminar yang diselenggarakan oleh Unsil bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Lembaga Penelitian Prancis untuk Timur Jauh itu membahas sejarah Galuh ditinjau dari berbagai kajian, antara lain epigrafi, filologi, arkeologi, numismatik dan sehagainya.
Untuk membuka pemahaman pembaca terhadap “Galuh”, “PR” menurunkan tulisan ahli sejarah, Drs. Atja. Tulisan ini berupa makalah yang juga disampaikan pada seminar di Tasikmalaya itu. Kami muat secara bersambung mulai hari ini. (redaksi)
Toponim suatu tempat sering sangat penting bagi suatu kajian serajah, karena di dalamnya terkandung nilai sejarah baik yang berhubungan dengan lingkungan alam maupun dengan kehidupan manusia yang menempatinya. Di samping itu penamaan suatu tempat merupakan ciptaan manusia yang sengaja dengan mempertimbangkan unsur-unsur lingkungan, mitologi, legenda, sejarah dan lain-lain. Itulah sebabnya di sini akan dicoba ditelusuri nama tempat dalam pasang surutnya, yang menjadi sorotan kini ialah “Galuh”, dan tempat lainnya yang diperkirakan ada kaitannya.
Seorang pakar yang telah memperhatikan dengan saksama perihal nama “Galuh” ialah mendiang Prof. Dr. R. Ng Poerbatjaraka (baca: Purbocoroko). Beliau menulis sebuah makalah secara khusus tentang Galuh dalam majalah “Bahasa dan Budaya”. Tahun III, No.2, December 1954, halaman 6-10, berjudul: “3 Galuh”.
Untuk mencari arti
leksikal, beliau membuka kamus Jawa (Gericke & Roorda 1901, II),
galuh, Kw. zva. putri orang bangsawan dan dewi (Skt.
galu, sejenis batu permata). KN nama kabupaten di dalam Keresidenan Cerbon, zaman dulu kota kerajaan. Di dalam kamus Purwodarminto;
galuh kl. (kesusastraan lama) ratna (intan); putri (anak raja). Di dalam
Kw. Bal. Ned. Wdb Van den Tuuk, kata
galuh diterangkan dengan panjang lebar, tetapi artinya: I. antara lain juga cuma mengelilingi arti putri dan permata (emas), II. Nama kerajaan di tanah Jawa (zaman Kuna).
Galuh sebagai nama sebuah kerajaan di Tanah Jawa zaman kuno, Prof. Poerbatjaraka menyebutkan :
I. Terdapat hampir di tiap-tiap Serat Babad yang menceritakan “zaman itu”. Beliau memberi contoh di dalam
Serat Babad No. 1 yang disimpan di Lembaga Bahasa dan Budaya (kini: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa), hlm. 257, tentang perangnya Raja Banjaransari yang bermusuhan dengan raja (jin) perempuan di Galuh.
II. Di dalam
Babad Tanah Jawi, sebagai negara Arya Bangah (ed. Meinsma-Olthof 1941).
III. Di dalam
Serat Aji Saka, sebagai Raja Sindula, ayah Sang Dewata-cengkar, Negara Galuh ini diceritakan ketika diserang perang oleh Dewata-cengkar, sekonyong-konyong
ilang menjadi
utan. (
Serat Aji Saka oleh CF Winter 1857).
IV. Di dalam Carita Parahiyangan, sebagai negara Raja Sanjaya. Sungguhpun cerita no. I, II, III itu cuma cerita sebagai dongeng pula, tetapi dongeng yang sangat mendekati cerita riwayat (
Riwayat Indonesia I 1952: 61).
V. Galuh ditambah Ujung, jadi Ujung-Galuh, nama tempat, yang dikatakan bula mengasingkan sang Jayakatwang, raja di Kediri oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit yang pertama (
Pararaton 1920).
VI. Ada nama Galuh pula yang ditambah awalan pra-, jadi Pragaluh, ialah nama desa atau daerah, yang terdapat pada batu tulis, yang terdapat di Desa Gandasuli (Kedu), yang masih terletak di tempatnya (De Casparis 1950: 62). Kabar inilah yang mempunyai derajat bahan epigrafi, yang di dalam ilmu pengetahuan sejarah sangat pentingnya.
VII. Galuh sebagai betul-betul nama ilmu bumi di Tanah Jawa, terdapat di dalam karangan CM Pleyte, seorang yang boleh dianggap ahli dalam ilmu Kesundaan, yang mengatakan bahwa Galuh sekarang ialah (ongeveer) Ciamis. (Pleyte 1913: (282).
Prof. Poerbatjaraka selanjutnya menunjuk kepada sebuah nama kampung: Begalon di sekitar Keraton Surakarta, menurut tradisi kampung itu dulu ditempati oleh pegawai tukang menggosok intan berlian. Katanya, asal-mulanya nama kampung itu tentu:
Pegalon, dari
Pegaluan dari
pegaluhan dari
galuh pula. Barangkali keterangan “tempat pegawai tukang menggosok intan-berlian” itu, setelah galuh diberi arti “permata”. Karena itu Prof. Poerbatjaraka mengajukan pertanyaan; mungkinkah bahwa kampung itu dulu ditempati oleh pegawai tukang membuat barang perak, barang perak upacara yang besar-besar seperti lancang, sumbul, bokor dan lain-lainnya, karena kampung itu sangat berdekatan dengan Kawatan. Sayangan dan “kemasan”.
Prof. Poerbatjaraka berpendapat, bahwa Galuh sebagai nama tempat, yang letaknya di Tanah Jawa tulen ada di arah barat, maka artinya tanah -, daerah -, atau Negara Galuh itu ialah tanah-, daerah -, atau Negara Perak.
Dalam karangan no. 4, berjudul
Bagelen. Perihal kata itu, beliau menunjuk kepada rangkaian bentuk dari kata:
Pegalon dari Pegalon, dari Pegaluan, dari Pegaluhan, dari
Galuh. Demikian juga nama Bagelen itu dari
Pagelen, dari
Pegalian, dari
Pegalihan, dari Galih. Adapun kata
Galih itu bentuk krama dari
Galuh. Prof. Poerbatjaraka memperingatkan, katanya, jangan dicampur
bentuk krama dengan
kata krama. Yang dimaksud dengan kata krama oleh beliau, ialah:
putra, krama,
anak ngoko;
griya krama,
omah ngoko. Sebagai temannya beliau menunjukkan beberapa rangkaian contoh:
pangguh; panggih; lungguh; linggih; sungguh; singgih; suruh; sirih. Maka bendasarkan beberapa contoh, Prof. Poerbatjaraka berkeyakinan, bahwa Pegalihan itu bentuk krama dari Pegaluhan, seperti juga Galih dari Galuh; dan Galih itu di dalam cerita “rakyat” Sunda memang nama negara zaman kuno, cuma saja ditambah Pakuan, menjadi Galuh Pakuan.
Dalam pada itu kesimpulan yang ditarik oleh Prof. Poerbatjaraka, bila keterangan tentang Galuh dan Bagelen digabung, maka sejarah daerah aliran Sungai Bagawanta – Serayu – Citanduy, zaman dulu ada di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh yang pusatnya ada di daerah Ciamis sekarang.
1. Bahwa untuk menelusuri perkembangan sejarah Galuh sebagai sebuah pusat kekuasaan raja-raja pada zaman dahulu, hampir dapat dikatakan tidak mungkin mendapat dukungan prasasti-prasasti atau peninggalan purba lainnya, demikian juga berita-berita asing, yang ada hanyalah beberapa naskah, yang tertua sampai kepada kita hanya beberapa buah berasal dari akhir abad ke-16 Masehi dan beberapa buah dari abad ke-17 Masehi. Berbeda dengan sistem penyalinan di daerah kebudayaan Bali, karena mereka masih sangat terikat kepada agama yang sama dengan isi naskah yang disalinnya, mereka berusaha menyalin naskah sepatuh mungkin, biarpun kesalahan kecil-kecil yang tidak mungkin mereka lakukan secara sadar. Sedangkan para penyalin di Jawa Barat menganut agama yang berbeda dengan isi naskah tentang kepercayaan yang lama, mereka merasa lebih bebas melakukan penyalinan kreatif, disesuaikan dengan kepentingan orang atau pembesar yang membiayainya.
Dalam kesempatan berbicara seputar Galuh kali ini, saya ingin mengetengahkan, beberapa naskah, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum, yang dianggap berisi semacam “sejarah”, dalam pengertian masa naskah itu ditulis, yang isinya sudah barang tentu terikat kepada “kode budaya” masyarakatnya.
Pengertian “sejarah” (atau “sajarah”) pada masa itu ialah
stamboom, bukan
geschiedenis atau
history. Tetapi “sejarah” pada waktu pendudukan Jepang dipakai pengganti istilah
geschiedenis, yang dilarang dipakai di dunia persekolahan pada masa itu, padahal yang lebih dekat artinya, ialah “tarikh”.
Dalam pemakaiannya zaman dulu istilah “sejarah”, dipertukarkan secara bebas dengan kata “silsilah”, yang di Filipina Selatan, disebut “tarsilah” (Majul 1977, 1989).
Istilah “sejarah” pada dasarnya merupakan semacam “catatan”, tentang baris keturunan yang tertulis. Salah satu fungsi yang utama, adalah untuk menelusuri leluhur seseorang atau keluarga hingga pada seorang tokoh yang terkenal pada masa yang lampau, mungkin seorang tokoh politik atau seorang guru agama. Kenyataan ini memberi kesan, bahwa karya “sejarah” demikian tidak dimaksudkan untuk tetap sebagai dokumen sejarah saja. Tetapi sebaliknya catatan garis keturunan itu berfungsi untuk mendukung pengakuan individu-individu dan sesuatu keluarga untuk memperoleh kekuasan politik atau menikmati hak-hak istimewa tertentu yang bersifat tradisional, atau paling tidak menikmati martabat yang lebih tinggi di antara sesama anggota masyarakatnya.
Dengan demikian untuk melayani tujuan-tujuan itu, maka “sejarah” harus dipelihara agar tidak ketinggalan zaman. Bila ditulis pada bahan-bahan yang dapat rusak, seperti kertas, maka isinya harus dilestarikan dengan menyalinnya pada kertas baru. Dengan demikian, usia bahan yang digunakan bukan merupakan petunjuk usia atau keotentikan catatan-catatan itu (Majul 1989: 98-9).
Kalau kita nanti menelaah beberapa jenis naskah yang saya anggap berisi “sejarah”, yang tampaknya bervariasi, maka janganlah dengan serta-merta beranggapan, sebagai dokumen yang berisi silsilah yang memperlihatkan suatu kesalahan. Sesungguhnya silsilah itu bisa berisi pemberian mengenai sebagian tokoh, nama-nama tempat dan data sebenarnya dari peristiwa masa lampau, tetapi juga dimasukkan unsur-unsur mitologis, karena dimaksudkan untuk memenuhi beberapa tujuan di luar fungsi genealogis yang bersangkutan. Mungkin saja untuk sesuatu tujuan beberapa nama disingkirkan, misalnya guna mencegah agar keturunan-keturunan tertentu tidak dapat menuntut haknya atas tahta.
2. Di bawah ini akap saya kupas beberapa naskah:
Kitab Waruga Jagat (untuk selanjutnya disingkat (
KWJ) hanyalah sebagian kecil saja dari sebuah
naskah, yang kini tersimpan di Museum Yayasan Pangeran Sumedang (YPS) di Sumedang. Bagian yang lainnya dari naskah tersebut merupakan jenis
parimbon, yang isinya terdiri atas bermacam-macam hal, sebagai catatan yang berhubungan dengan ilmu nujum, dalam sastra Melayu disebut
pestaka (vademecum).
Bahan naskah bukan dari kertas, melainkan dari bahan yang kita kenal dengan sebutan
daluwang (Jawa :
dluwang), yang terbuat dari serta kulit pohon “saeh”.
Naskah itu berukuran kuarto. Bagian yang disebut
KWJ tertulis dengan huruf
pegon (Arab-Jawa), dengan bahasa Jawa-Sunda, tebalnya hanya terdiri atas 12 lembar.
Kecuali sebuah naskah yang tersebut di atas, di museum
YPS; tersimpan juga sejumlah naskah yang lain, di antaranya yang sangat menarik, ialah
Silsilah Keturunan Bupati-bupati Sumedang, tertulis dengan huruf
pegon (Arab-Jawa), dengan bahan kertas Eropa, berukuran folio, ditulis atas nama Raden Adipati Suryalaga II, yang pernah menjadi bupati di Bogor, Karawang dan Sukapura, masa hidupnya sezaman dengan Pangeran Kornel, pada abad 18-19 Masehi.
Sebuah naskah lagi dengan bahan daluwang dalam keadaan sangat rusak, pada mulanya sukar ditebak apa isinya, mempergunakan bahasa dan askara Jawa-Sunda yang sulit dibaca, dalam bentuk puisi/kidung (Sunda :
wawacan). Pada awal tahun 1972 bersama Drs. Didi Suryadi almarhum, saya berusaha untuk dapat membaca dan mengetahui garis-garis besar isinya. Akhirnya ada bagian yang terbaca perihal uraian
percintaan antara Mundingsari dengan putri Amberkasih di Negara Sindangkasih. Setelah bagian itu diketahui, barulah dapat ditentukan, bahwa naskah yang sangat rusak itu adalah salah satu versi dari apa yang disebut dengan
Babad Siliwangi, mungkin salah satu salinannya adalah
Babad Siliwangi yang tersimpan di Museum Nasional (kini ditempatkan di Perpustakaan Nasional Jakarta), dengan judul yang sama turunan naskah itu dikerjakan oleh Raden Panji Surya Wijaya, Betawi, 1866 (Poerbatjaraka 1933: 293). Naskah tersebut telah disinggung pula dalam
Cariosan Prabu Silihwangi yang disunting oleh Sunarto & Viviene Sukanda-Tessier (1983). Pada dasarnya
KWJ menguraikan mata rantai para tokoh yang pernah memegang peranan penting dalam sejarah, yang diwarnai oleh kepercayaan yang diselimuti dalam suasana lslamisasi khususnya di Jawa Barat.
Di dalam
KWJ, selain dapat kita telaah deretan penguasa-penguasa yang menurut kepercayaan masyarakat tradisional pernah berkuasa di tanah air kita, juga dihubungkan dengan para penguasa yang pernah memegang peranan dalam penyebaran agama di dunia Islam, yang menurut anggapan penulisnya, kesemuanya bertalian keluarga satu sama lain. Demikianlah makna yang sesungguhnya dan istilah
Waruga Jagat.
Jika kita perhatikan arti kata
waruga, maka perlu saya ketengahkan akan makna yang diberikan oleh CM Pleyte dalam karyanya: “De Patapaan Adjar Soekaresi,
andere gezegd de kluizenarij op de Goenoeng Padang”, TBG, jilid 55, hal. 380, catatan 2, dia mencoba mengupas pengertian
waruga, dalam rangka membicarakan naskah
Carita Waruga Guru. Pleyte menulis, makna
waruga: belichaming (penjelmaan, pengejawantahan), lichaam (badan, tubuh), dan lijf (badan, tubuh). Dari ketiga arti yang diberikan oleh Pleyte itu, yang lebih mendekati ialah
penjelmaan atau
pengejawantahan. Pengejawantahan tokoh-tokoh, yang memegang peranan penting di dunia, ditinjau dari wawasan dan sudut pandangan penulis.
Kata
waruga dalam BahasaJawa Kuno sebagaimana dicatat oleh Prof. Zoetmulder (1982: 2211), a
Mind of building (“bale”? hall, pendopo?), sedangkan pada tempat sebelumnya dicatat pula kata:
waruga I a part. official or functionary. Van der Tuuk (1901) mencatat tentang arti
waruga dalam beberapa bahasa yang bersaudara, dalam Bahasa Bali,
waruga : bale, Sasak,
barugaq; bale; Bima,
paruga: rumah-rumahan di atas kuburan; Sangir,
bahugha, Rejang, Bugis, Makasar,
baruga; Lampung,
parugan, berugu (baca:
baruga), bangunan berbentuk kubah atau anjung di muka atau di samping rumah tempat wanita bertenun; Bengkulu,
brogo- ruangan tempat duduk-duduk.
3. Pada halaman 12, ditulis
kolofon, berbunyi:
tamat kitab waruga jagat tutug ing tulis ing malem Salasa wulan Rayagung ping 8 tahun alip 1117 hijrah. kang gaduh mas ngabehi prana. (Tamat Kitab Waruga Jagat, selesai ditulis pada Senin malam, bulan Zulhijjah, tanggal 8, Tahun Alip, 1117 Hijrah (23 Maret 1706 Masehi), kepunyaan Mas Ngabehi Prana.
Kitab Waruga Jagat ini selanjutnya dilengkapi dengan paririmbon, terdiri atas :
(a) Salinan Kitab Barzanji dan Doa Maulud Nabi; (b) Uraian tentang kebiasaan bersawah; (c) Uraian tentang uga zaman.
Kitab Waruga Jagat versi lain kini tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, (Juyboll 1912: 7071, CXXVI. (Cod. 239 (Bijb. Gen.), dalam sebuah berkas, yang terdiri atas empat bagian, tebal 44 halaman, terdiri atas :
(a)
Waruga Jagat (hlm. 1-23). daftar rangkaian garis keturunan dari
Adam dan
Nuh (Enoh) sampai kepada
Pangeran Saba Kingkin (Hasanuddin), bahasanya lebih bersifat Jawa daripada Sunda
(meer Javaansch dan
Soendaneesch); (b) Waruga jagat atau
Babad Pajajaran (hlm. 23-33), mengenai daftar silsilah yang sama, tetapi ditulis dalam bahasa Sunda dan sebagian membicarakan tentang agama Islam;
(c) Dongeng Ki Basra, isinya sebuah cerita rakyat dalam bahasa Sunda, dan (d) Isinya tujuh buah teka-teki dalam bahasa Sunda dengan penyelesaiannya. Juyboll tidak menyebut ukuran naskah, bahan dan huruf yang digunakan, demikian pula tahun penulisannya tidak disebutkan.
4. H. Said Raksakusumah almarhum, menggarap sebuah naskah, yang berjudul:
Kitab Pacakaki Masalah Karuhun Kabeh, sebuah naskah yang dimiliki oleh masyarakat Cisondari, Bandung Selatan. Hasil garapannya, terjemahan dan pembahasan secara singkat dalam bahasa Indonesia (1973). Naskah itu ditulis dalam huruf pegon dengan bahasa Sunda-Jawa, tetapi tidak
menyebutkan bahannya apakah kertas atau daluwang.
Dalam kolofon pada halaman terakhir kebetulan dicatat olehnya, sebagai berikut:
“Kitab Pacakaki Masalah Karuhun Kabeh…. dipedalkeunana di Pamarican tanggal 15 bulan…. Rabu akhir tahun Dal Hjrah 1271. Karena nama bulan tidak terbaca, – mungkin naskah rusak – Tahun 1271 Hijrah = 1854/5 Masehi.
H. Said Raksakusumah mencatat isi kitab itu, meliputi: (a) Tulisan Sejarah; (b) Sifat 20; (c) Kumpulan Du’a-du’a di antaranya Du’a Nurbuat. Selanjutnya disebutkan, penulis menguraikan sejarah di Pulau Jawa sesuai dengan pengertian kata sejarah pada zamannya, yaitu memberikan urutan nama (silsilah) orang-orang yang memegang pimpinan kemasyarakatan, baik politis maupun spiritual. (Said Raksakusumah 1973: 1).
Kenyataan yang kita hadapi menunjukkan bahwa penulisan
KWJ, pada tahun 1117 Hijrah (1706 Masehi), tidak menyebut tempat ditulisnya, mungkin di Sumedang, sedangkan Kitab Pacakaki Masalah Karuhun Kabeh ditulis tahun 1272 Hijrah (1854/5 Masehi) di Pamarican, Ciamis Selatan. Mengingat waktu penulisannya berjangka ± 150 tahun, jarak tempat antara Sumedang dan Pamarican demikian jauhnya, kita bisa menduga, bahwa penulis di Pamarican tidaklah menggunakan
KWJ Sumedang sebagai contoh.
* * *
 Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.
Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.  Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949. Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.
Pada masa pendudukan Jepang istilah Afdeeling diganti dengan Bun, Onder Afdeeling disebut Gun, Zelf Bestuur disebut Sun, Mukim disebut Kun dan Gampong disebut Kumi. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949. Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km2 dan berpenduduk sebanyak 477.745 jiwa membawahi 27 kecamatan.
Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km2 dan berpenduduk sebanyak 477.745 jiwa membawahi 27 kecamatan.  B&W Photography
B&W Photography Animals
Animals Abstract
Abstract Scenic
Scenic Framed Art
Framed Art Canvas Art
Canvas Art Tapestries
Tapestries Wall Murals
Wall Murals Giclee Prints
Giclee Prints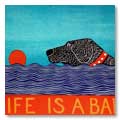 Limited Edition
Limited Edition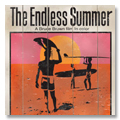 Wood Signs
Wood Signs Photographic Prints
Photographic Prints People
People Botanical
Botanical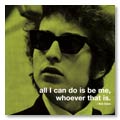 Music
Music Maps
Maps Marvel Collection
Marvel Collection LIFE
LIFE Editor's Picks
Editor's Picks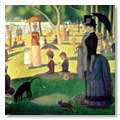 Museum Art
Museum Art National Geographic
National Geographic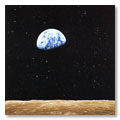 Art.com Exclusives
Art.com Exclusives Disney
Disney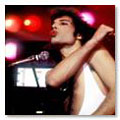 Ron Pownall
Ron Pownall Lonely Planet
Lonely Planet Vintage Hollywood
Vintage Hollywood Eco-Friendly Art
Eco-Friendly Art Associated Press
Associated Press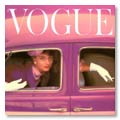 Vintage Magazines
Vintage Magazines Warhol Premium
Warhol Premium Hallmark
Hallmark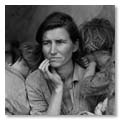 Library of Congress
Library of Congress Vincent Van Gogh
Vincent Van Gogh Claude Monet
Claude Monet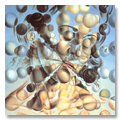 Salvador Dali
Salvador Dali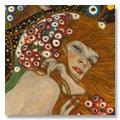 Gustav Klimt
Gustav Klimt Andy Warhol
Andy Warhol Pablo Picasso
Pablo Picasso Wassily Kandinsky
Wassily Kandinsky  Leonardo Da Vinci
Leonardo Da Vinci Georgia O’Keeffe
Georgia O’Keeffe Don Li-Leger
Don Li-Leger Mark Rothko
Mark Rothko Henri Matisse
Henri Matisse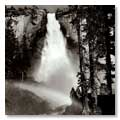 Ansel Adams
Ansel Adams Leonetto Cappiello
Leonetto Cappiello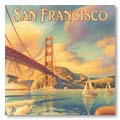 Kerne Erickson
Kerne Erickson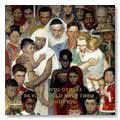 Norman Rockwell
Norman Rockwell Coastal
Coastal Architecture
Architecture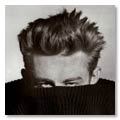 People
People World Culture
World Culture Black & White
Black & White Color
Color Sepia
Sepia Panoramic
Panoramic Wall Mural
Wall Mural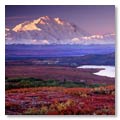 Premium Prints
Premium Prints Limited Editions
Limited Editions Framed Photography
Framed Photography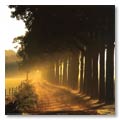 Scenic
Scenic Astronomy
Astronomy Floral
Floral Animals
Animals